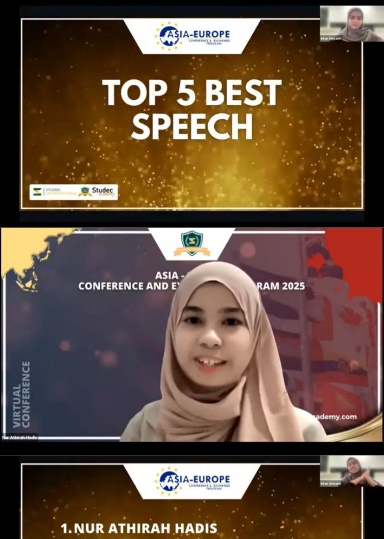Infografik Psikodukasi bertajuk “Bahaya Self Diagnose di TikTok”
Sumber: Dok. Pribadi
Peserta Kuliah Kerja Profesi (KKP) Pusat Layanan Psikologi (PLP) Fakultas Psikologi (FPsi) Universitas Negeri Makassar (UNM), sukses melaksanakan kegiatan psikoedukasi bertajuk “Bahaya Self Diagnose di TikTok” yang disebarkan melalui media sosial Instagram.
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan literasi kesehatan mental, khususnya di kalangan generasi muda yang aktif menggunakan media sosial, terhadap bahaya praktik self-diagnose atau mendiagnosis diri sendiri tanpa bantuan profesional, yang marak terjadi di platform seperti TikTok.
Melalui akun Instagram @kkpplp2025.jpg, Tasha Nurhaliza membagikan poster edukatif berjudul “Hati-hati Self-Diagnose di TikTok” yang berisi penjelasan ringan namun ilmiah tentang defenisi self-diagnose, bahaya self-diagnose, faktor yang mendorong tren tersebut di media sosial, serta tips membedakan informasi psikologi yang valid dan tidak valid. Poster ini dirancang dengan visual menarik dan pesan reflektif agar mudah dipahami serta mendorong audiens berpikir kritis.
Mahasiswi yang akrab disapa Tasha menjelaskan bahwa fenomena self-diagnose di TikTok kerap muncul karena algoritma media sosial menampilkan konten psikologi yang populer, meskipun seringkali disampaikan oleh non-profesional atau hanya berdasarkan pengalaman pribadi.
“Self-diagnose bisa menyesatkan, karena diagnosis psikologis itu kompleks dan harus melibatkan pemeriksaan mendalam oleh tenaga profesional. Salah mendiagnosis bisa membuat seseorang merasa lebih buruk atau bahkan salah memilih penanganan,” jelas Tasha.
Postingan edukasi ini memperoleh 74 likes, dan sebanyak 31 responden berusia 18–30 tahun bersedia mengisi survei evaluasi melalui Google Form yang dibagikan secara personal.
Berdasarkan hasil survei, 100% responden menyatakan memahami isi poster dan merasa bahwa poster tersebut bermanfaat, informatif, serta mudah dipahami. Sebagian besar menyampaikan bahwa psikoedukasi ini berhasil meningkatkan pemahaman mereka tentang bahaya self-diagnosis dan pentingnya mencari bantuan dari tenaga profesional dalam masalah kesehatan mental.
Temuan ini menunjukkan bahwa psikoedukasi berbasis media visual seperti poster dapat menjadi sarana efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu-isu kesehatan mental yang sering disalahartikan di media sosial. Namun, terdapat beberapa masukan dari responden terkait ukuran font yang dianggap terlalu kecil dan desain visual yang masih bisa ditingkatkan agar lebih menarik dan komunikatif.
Tasha juga menyampaikan beberapa keterbatasan kegiatan ini, seperti jumlah partisipan yang relatif sedikit sehingga membatasi generalisasi hasil, tidak adanya pre-test yang membuat data bersifat perseptual, dan potensi bias karena hubungan personal antara responden dan pembuat konten.
“Ke depan, saya berharap kegiatan serupa dapat dilengkapi dengan pre- dan post-test untuk mengukur efektivitas secara objektif, serta melibatkan partisipan yang lebih besar dan beragam. Saya juga berencana meningkatkan kualitas visual berdasarkan saran responden agar pesan bisa tersampaikan dengan lebih kuat,” ungkap Tasha.
Sebagai penutup, Tasha menekankan bahwa literasi digital tentang kesehatan mental sangat penting di era informasi yang serba cepat namun tidak selalu akurat.
“Psikoedukasi seperti ini bisa menjadi jembatan awal dalam membantu masyarakat memilah informasi serta mendorong perilaku yang lebih bijak dan sehat dalam menyikapi isu-isu psikologis yang beredar di media sosial,” tutupnya.